Di Indonesia, seperti juga di negara lain, basa-basi memiliki akar yang kuat dalam tradisi sopan santun dan norma sosial. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pergeseran nilai, beberapa bentuk basa-basi yang dahulu dianggap sopan kini dipertanyakan oleh generasi muda. Contoh nyata adalah pertanyaan semacam “Kapan akan menikah?” atau “Jangan lupa bawa oleh-oleh, ya?” yang kerap dilontarkan di lingkungan keluarga atau pertemuan sosial.
Keluhan mengenai
pertanyaan-pertanyaan tersebut belakangan ini sering muncul di media sosial. Para
netizen muda menganggapnya tidak lagi relevan dengan gaya hidup saat ini dan
bahkan terkesan mengatur hidup mereka. Kritik ini mencerminkan adanya perubahan
kebutuhan komunikasi di era digital ketika individualitas dan privasi lebih
dihargai.
Selain itu,
perkembangan urbanisasi dan globalisasi juga memicu munculnya gaya komunikasi
baru yang menekankan keautentikan dan spontanitas, berbeda dengan ritual
komunikasi yang kaku di masa lalu.
Basa-basi atau
obrolan ringan (small talk) sering dianggap remeh yang hanya melibatkan
topik sepele. Namun, di balik kesederhanaannya terdapat fungsi sosial yang
sangat penting. Sejak Bronisław Malinowski memperkenalkan konsep komunikasi
fatik—yaitu komunikasi yang bertujuan membangun ikatan sosial melalui
pertukaran kata-kata yang tampak tidak informatif—basa-basi telah menjadi
elemen kunci dalam interaksi antarmanusia.
Obrolan ringan ini
berperan sebagai perekat hubungan sosial yang membantu menciptakan rasa
kebersamaan, mengurangi keheningan yang membuat canggung, dan bahkan
memfasilitasi transisi menuju diskusi yang lebih dalam.
Di era modern,
terutama dengan kemunculan teknologi digital dan globalisasi, praktik basa-basi
mengalami transformasi. Bentuk-bentuk tradisional yang pernah dianggap sopan
dan relevan kini sering dipertanyakan, terutama oleh generasi muda.
Antara Universalitas
dan Kekhasan Budaya
Meskipun tampak
remeh, basa-basi merupakan kegiatan metakomunikatif yang tidak hanya berfungsi
untuk mengisi kekosongan atau menghindari keheningan, tetapi juga sebagai alat
untuk membangun dan memelihara hubungan sosial. Secara universal, kebutuhan
untuk berkomunikasi dan merasakan kehangatan hubungan antarpribadi merupakan
aspek fundamental dalam kehidupan manusia. Berbasa-basi dapat mempermudah terbentuknya
interaksi awal dengan memberikan sinyal bahwa kedua pihak memiliki niat untuk
bersosialisasi secara positif.
Di sisi lain, bentuk,
isi, dan cara penyampaian basa-basi sangat dipengaruhi oleh konteks budaya dan sejarah.
Misalnya, di dalam beberapa budaya, topik-topik tertentu seperti cuaca,
olahraga, atau kegiatan akhir pekan sering dijadikan pembuka percakapan. Sedangkan
di budaya lain, pertanyaan personal yang terlalu mendalam bisa dianggap tidak
sopan.
Di Indonesia, tradisi
komunikasi yang kuat dan nilai-nilai kesopanan memiliki karakteristik
tersendiri. Meskipun ada norma untuk saling menyapa dan bertanya kabar,
generasi muda kini mulai mempertanyakan relevansi beberapa ungkapan yang selama
ini dianggap formal atau bahkan mengandung stereotipe. Mereka kini cenderung
tidak setuju lagi mendapat pertanyaan basa-basi, seperti “Mau pergi ke mana?”–dari
seorang penumpang yang duduk di jok sebelah dalam angkutan umum, “Lagi menyapu,
ya?”–yang dilontarkan seseorang pada saat mereka tengah membersihkan halaman
rumah, dan sebagainya.
Baca juga: Seni berbasa-basi supaya tetap relevan dengan perbedaan budaya dan perubahan zaman
Basa-basi sebagai
Alat Bekerja Sama
Selain fungsi sosial
dalam konteks personal, basa-basi memiliki peran penting dalam dunia
profesional dan komersial. Dalam lingkungan kerja, obrolan ringan dapat
menciptakan suasana yang lebih ramah dan kolaboratif, sehingga meningkatkan
kepercayaan di antara rekan sejawat.
Di
tempat kerja, basa-basi sering digunakan sebagai pemecah kebekuan (ice
breaker) pada awal pertemuan atau dalam sebuah rapat resmi. Dengan
memberikan kesempatan bagi para kolega untuk saling mengenal secara informal,
suasana kerja menjadi lebih kondusif dan tim dapat bekerja sama dengan lebih
harmonis.
Dalam
hubungan bisnis, basa-basi berfungsi sebagai alat untuk membangun loyalitas
pelanggan. Ketika pelaku usaha memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara
personal dan hangat, mereka dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan
membuat mereka merasa lebih nyaman. Pada gilirannya, ini akan membantu
transaksi berhasil dan menjalin hubungan jangka panjang dengan pelanggan.
Teknologi
digital telah mengubah cara kita berkomunikasi. Basa-basi kini juga
terjadi melalui media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform video call.
Meski formatnya berubah, esensi untuk menciptakan hubungan yang menyenangkan
dan membangun jaringan tetap sama.
Maka,
basa-basi adalah fenomena komunikasi yang jauh lebih kompleks daripada sekadar
obrolan ringan. Basa-basi merupakan kegiatan metakomunikatif yang
mendasar untuk membangun ikatan sosial dan menjaga kohesi dalam interaksi
antarindividu.
Strategi komunikasi
yang adaptif dan sensitif terhadap perubahan generasi menjadi kunci untuk
memastikan bahwa basa-basi tetap relevan dan mampu memenuhi kebutuhan
interaksi sosial di masa depan. Dengan memahami evolusi praktik komunikasi ini,
kita dapat merancang pendekatan yang lebih inklusif dan efektif dalam berbagai
situasi—baik dalam kehidupan pribadi, profesional, maupun lintas budaya.
Dalam dunia yang
semakin terhubung secara digital, fleksibilitas dalam berkomunikasi menjadi
kompetensi utama. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menyesuaikan bentuk
dan isi basa-basi dengan dinamika zaman. Mengganti pertanyaan atau
ungkapan yang terkesan kaku dengan yang lebih relevan dan bersahabat, terutama
dalam konteks interaksi antargenerasi dan antarbudaya, akan membantu mengurangi
kesalahpahaman dan memperkuat hubungan sosial.
Sebagai alternatif,
alih-alih mengajukan pertanyaan “Kapan akan menikah” kepada keponakan yang
masih melajang, kita bisa bertanya “Apa rencanamu tahun ini?”. Frasa ini
bersifat terbuka dan menghormati pilihan lawan bicara untuk berbagi informasi
pribadi atau tidak.
Daripada meminta teman
“Jangan lupa bawa oleh-oleh, ya?”, lebih baik berkata “Selamat liburan. Ditunggu
cerita liburannya.” Dengan mengganti fokus dari barang (oleh-oleh) ke kisah
perjalanan, pertanyaan ini mengedepankan nilai momen dan pengalaman–sesuai
dengan gaya hidup anak muda yang lebih menghargai cerita daripada benda fisik.
Ketimbang “Mau pergi
ke mana?”, lebih baik diganti dengan “Ada rencana seru hari ini?” yang dapat
mengundang lawan bicara untuk berbagi cerita soal kegiatannya atau destinasi tujuan
tanpa harus menyebut “pergi” secara eksplisit.
Kita bisa bertanya,
“Wah, sedang sibuk, ini?”–yang lebih informal, tetapi positif–sebagai pengganti
pertanyaan “Lagi menyapu, ya?”.
Pertanyaan alternatif
ini pada dasarnya bermaksud lebih menghormati privasi dan otonomi orang lain.
Selain itu, pertanyaan-pertanyaan tersebut bersifat lebih terbuka sehingga memungkinkan
percakapan berlangsung lebih substansial dan tidak terlalu dangkal. Dengan kata
lain, basa-basi modern berfokus pada pembentukan hubungan nyata daripada hanya mengisi
ruang percakapan. Sebaliknya, pertanyaan basa-basi konvensional mungkin saat
ini dianggap mengganggu dan tidak berarti lagi, seolah pepesan kosong.
Pada akhirnya, basa-basi
bukan sekadar obrolan ringan semata. Ia merupakan cerminan nilai, norma, dan
identitas budaya yang terus berubah. Denagn demikian, basa-basi tetap menjadi
alat yang efektif dalam membangun dan memelihara hubungan antarindividu.

Gunakan format APA berikut jika kamu mengutip tulisan ini:
Prayoga, E. A. (2025, March 03). Basa-basi Anak Muda: Menentang Konvensi, Membangun Koneksi. Blog Elga Ahmad. Diakses pada [tuliskan tanggal akses], dari https://blog.elga-ahmad.com/2025/02/dubbing-prancis.html.




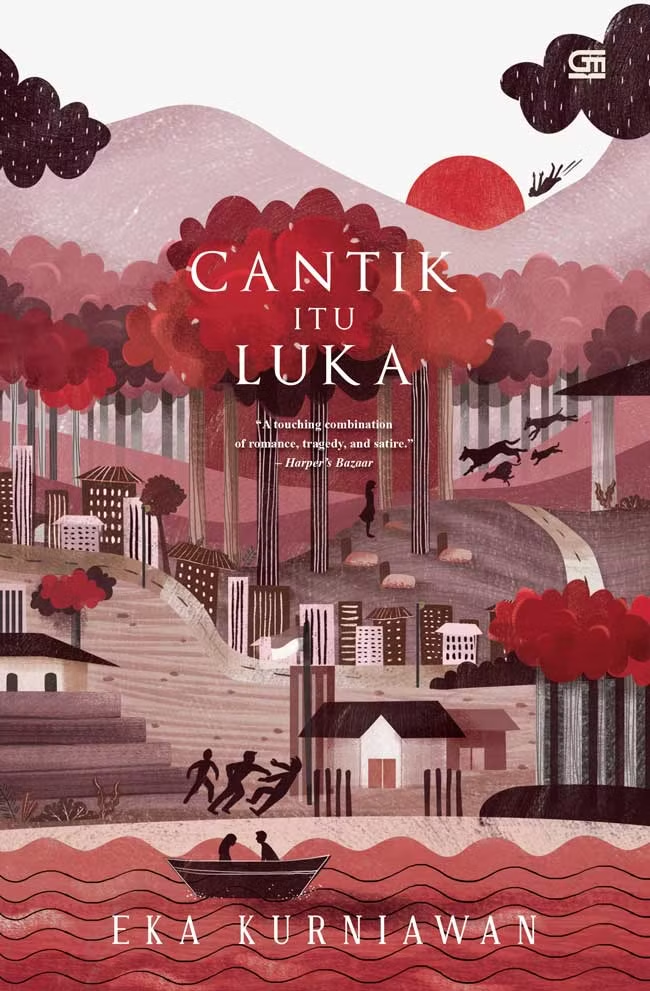













Media Sosial
Gunakan media sosial berikut untuk terhubung dengan Elga Ahmad.